

John Maxwell, seorang pendeta dan pakar kepemimpinan, membuat satu pernyataan bahwa “Leadership is not about titles, position or flowcharts, it is about one life influencing others”. Kepemimpinan bukanlah suatu jabatan maupun posisi atau struktur, melainkan bagaimana hidup seseorang mempengaruhi kehidupan orang lain.
Bagaimana kalau ada pemimpin yang kinerjanya sangat baik, tetapi cara dan tindakannya justru tidak menjadi teladan bagi orang lain, bahkan menjadi musibah atau tragedi bagi kehidupan orang yang dipimpinnya?
Hal di atas begitu sering terjadi, sehingga kita kerap menemukan pemimpin berkinerja luar biasa, tapi tidak demikian dengan karakternya. Apalagi sebagai anak Tuhan, kita seakan dituntut harus menjadi pemimpin seperti Kristus. Namun kenyataannya hidup kita dipengaruhi oleh budaya dan masa lalu yang membentuk karakter kita. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri.


Daniel Goleman yang terkenal dengan konsep dan pemikiran pentingnya mengenai kecerdasan emosional (emotional intelligence) berkata, apabila seorang pemimpin tidak memiliki kecerdasan emosional, maka pemahaman dirinya akan sangat rendah dan pengendalian emosinya menjadi tidak baik. Akibatnya, kemampuan membina hubungan akan rusak dan ia akan kehilangan empati. Pemimpin seperti ini tidak akan mampu memimpin dengan baik dan langgeng, sekalipun dia sangat cerdas.
Bagi seorang pemimpin, kecerdasan emosional sangat penting dalam menentukan suksesnya suatu kepemimpinan dan kualitas keputusan yang diambilnya. Perkataan dan tindakan yang diperbuat akan begitu mudah mempengaruhi kehidupannya saat ini maupun kelak. Demikian juga terhadap perusahaan yang dipimpinnya.
Saat ini kita dapat melihat bagaimana media sosial dan jejak digital merefleksikan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Hal ini begitu penting dan menentukan banyak langkah ke depan, termasuk pembentukan persepsi terhadap seorang pemimpin.
Sebagai umat Kristen tentunya kita paham dengan pesan rasul Paulus kepada jemaat Korintus:
“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru; yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Korintus 5:17).
Apabila kita memakai pemahaman ayat ini dalam konteks emosional, sesungguhnya kita adalah manusia baru. Pembentukan karakter akibat masa lalu atau kepahitan atau kepribadian kita tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk tidak mampu mengendalikan emosi.
Lalu, bagaimana cara praktis seorang pemimpin dalam membangun kecerdasan emosionalnya? Goleman dalam tulisannya di Harvard Business School membaginya ke dalam dua kuadran: paham diri (self awareness) dan kendali diri (self management). Intinya, ada suatu kesadaran yang disertai dengan tindakan yang harus diambil dalam diri kita. Kesadaran dimulai dengan memahami diri kita, masa lalu kita, dan memahami makna manusia baru yang telah ditebus oleh Kristus yang memampukan kita mengendalikan emosi diri.
Apabila kita mampu mengendalikan diri, maka akan lebih mudah untuk memiliki empati yang membuat kita memberi perhatian pada aspek sosial (social awareness) dan membuat langkah tindakan kita dalam membangun hubungan (relationship management) dengan pihak eksternal.
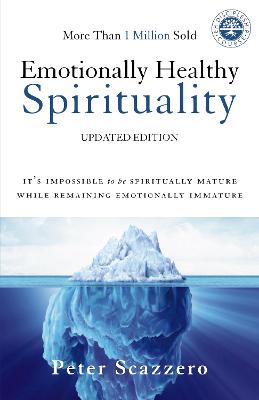
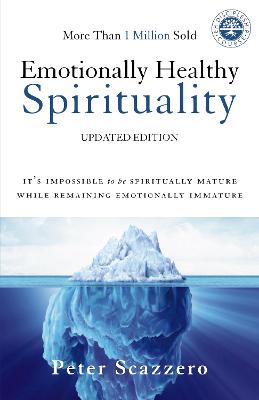
Peter Scazerro dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality juga membahas bagaimana seorang bisa memiliki kesehatan emosi secara spiritual. Langkah pertama dimulai dengan menerima dan memahami emosi dalam diri kita, yang akan memampukan kita memiliki empati dan menjaga hubungan dengan pihak lain. Scazerro juga menekankan betapa pentingnya tidak menyakiti diri sendiri walaupun memiliki masa lalu yang kelam, tetapi lebih mencari cara bagaimana memahami dan dapat mengekspresikan semuanya dalam satu komunikasi yang baik. Hal ini penting agar kita dapat memahami kelemahan dan kekuatan kita serta batasan diri kita dalam menghadapi tekanan emosi. Semuanya itu akan membuat kita lebih bijak dan dewasa dalam penyelesaian konflik.
Peran kepemimpinan merupakan suatu peran dari hidup yang memberikan pengaruh positif pada orang lain. Hal ini tidak dapat lepas dari kehidupan emosional kita yang berarti juga tidak dapat lepas dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukan suatu drama atau hal berlebihan, melainkan satu area manajemen yang membentuk kualitas kepemimpinan dan kualitas pengambilan keputusan.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi (Filipi 2:1-4) memberikan satu acuan dalam kepemimpinan. Bermula dari kesatuan hidup bersama, Roh Kudus yang memampukan kita menjaga persatuan dalam kasih, mengutamakan kerendahan hati, dan memfokuskan diri untuk satu tujuan, yakni kemuliaan Tuhan. Intinya adalah bagaimana kita menempatkan fokus dan pemikiran pada orang lain; menganggap orang lain lebih diutamakan dari diri kita dan bukan ego kita.
Apapun peran kita di area kepemimpinan, kiranya kita semua diingatkan bahwa semua yang kita miliki dan lakukan adalah anugerah Tuhan. Biarlah pernyataan yang disampaikan oleh seorang pemimpin gereja Thomas S. Monson dapat mengingatkan kita bahwa, “Ketika iman menggantikan keraguan dan ketika pelayanan tanpa pamrih menghilangkan upaya mementingkan diri sendiri, kuasa Tuhan yang akan membawa kehendak-Nya digenapi.”
Pada akhirnya, kiranya kita semua dimampukan untuk terus membangun kecerdasan emosi kita dalam kehidupan, baik dalam keluarga, pelayanan, dan kehidupan profesional kita.
Kehidupan masa lalu kita yang mempengaruhi karakter kita bukanlah menjadi suatu kendala. Jangan pula menjadikannya sebagai batu sandungan atau batasan dalam diri kita. Kita sekarang adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita diberikan hikmat untuk belajar dan terus diasah untuk mampu mengubah diri kita dengan penyertaan Roh Kudus yang diberikan Bapa. Tuhan Yesus memberkati.






No Comment! Be the first one.