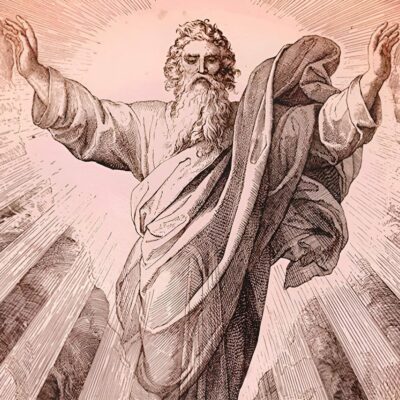Beberapa bulan lalu, saya dikirimi sebuah cuplikan video tentang seorang rohaniwan, sebut saja namanya A, yang menceritakan bahwa khotbah lisannya dicuplik plek-plek (sama persis) oleh rohaniwan lain, tanpa sepengetahuannya, menjadi sebuah karya tulis di internet. Tanpa sepengetahuannya juga berarti tidak ada keterangan bahwa tulisan itu merupakan saduran atau ringkasan atau bersumber dari khotbah si A.
Weleh weleh, saya cukup kaget melihat cuplikan tersebut. Pekerjaan saya sebagai dosen memang akrab dengan aktivitas skrining jiplak-menjiplak, atau istilah umumnya plagiarisme. Skrining plagiarisme rutin kami lakukan pada tiap tulisan ilmiah maupun bahan ajar kami. Mengapa? Alasan yang paling sederhana adalah karena plagiarisme sama dengan MENCURI. Wah, masak sih?
Coba kita simak definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Plagiat adalah “pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan”.1 Setelah membaca definisi ini, saya rasa Anda akan setuju dengan pernyataan saya tentang MENCURI.
Oh ya, Anda lihat tanda petik “…” dan 1 yang saya gunakan? Nah, ini adalah salah satu cara menghargai KBBI ketika saya mencuplik suatu definisi di lamannya. Kalau tidak, KBBI bisa menuntut saya karena cuplak-cuplik seenaknya. Seserius itu ya? Ya. Plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi perdata maupun pidana.
Plagiarisme memang bukan hal yang baru di dunia akademis maupun seni. Satu kasus yang cukup menghebohkan adalah mundurnya menteri pertahanan Jerman, Karl-Theodor zu Guttenberg, pada 2011 karena kasus plagiarisme disertasi Doktoral di bidang hukum.2 Universitas Bayreuth, tempat sang menteri mengenyam pendidikan S3, mencabut gelarnya dan ia pun mundur dari jabatan pemerintahan.
Dua tahun kemudian, Annette Schavan, menteri Pendidikan di negara yang sama juga terkena kasus serupa: plagiarisme, dengan konsekuensi yang sama pula: mundur dan pencabutan gelar akademik.3
Kok Jerman semua? Ini bukan karena di sana banyak pencuri, tetapi karena di sana penanganan plagiarisme sangat serius.
Bagaimana di dunia seni? Saya ingin Anda bandingkan dua buah lagu pop barat: Got to Give It Up dari Marvin Gaye dan Blurred Lines dari Robin Thicke. Dari intronya kok mirip ya? Dan kemiripan ini yang membuat Pak Robin dan kawan-kawan harus merogoh kocek jutaan dolar ke keluarga Pak Marvin atas perintah pengadilan setempat.4
Baik di dunia ilmiah dan seni, karya harus dijunjung tinggi dan dianggap serius. Saking seriusnya, seseorang dapat dinilai melakukan plagiarisme atas dirinya sendiri. Ini yang dikenal dengan auto atau self-plagiarism. Kok begitu? Ya misalnya saya mengeluarkan tulisan di 2014, lalu saya mengutipnya dalam tulisan saya pada 2018 tanpa memberikan keterangan sesuai aturan. Ya nggak boleh, itu namanya mencuri juga. Asyik ya?
Nah, sekarang mari kita kembali ke persoalan rohaniwan A dan khotbahnya yang plek-plek dicuplik. Ada suara yang menyatakan: tapi ini kan buat pelayanan, bukan untuk keuntungan pribadi. Saya sih kurang setuju dengan pernyataan ini. Ya kan bisa tetap minta izin ya? Jadi tulisan itu nanti tetap atas nama rohaniwan A, tetapi di laman orang lain. Penafsiran dan analisis Alkitab itu kan juga karya pemikiran seseorang? Jadi harus tetap dihargai dan tetap dianggap sebuah karya. Karya apa? Ya karya pemikiran. Plagiarisme itu bukan tentang tujuannya, tapi pengambilan karyanya.
Jadi teman-teman Nafiri, jika dari kecil kita sudah mengenal Hukum Taurat ke-8, maka kita harus juga terus belajar untuk menghindari plagiarisme di kehidupan kita sehari-hari.
Referensi:
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Plagiat [Internet]. Indonesia: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 2024 [akses pada 3 Agustus 2025]. Tersedia di https://www.kbbi.web.id/plagiat
2 Chelsom-Pill C. Guttenberg guilty [Internet]. Bonn: Deutsche Welle; 2011 [akses pada 3 Agustus 2025]. Tersedia di https://www.dw.com/en/university-says-ex-defense-minister-deliberately-cheated-on-thesis/a-15056863
3 Werkauser N. Plagiarism affair [Internet]. Bonn: Deutsche Welle; 2013 [akses pada 3 Agustus 2025]. Tersedia di https://www.dw.com/en/a-chronology-of-the-schavan-plagiarism-affair/a-165891714 Seeman S. Blurred lines of copyrights [Internet]. Texas: University of Texas at Austin; 2025 [akses pada 3 Agustus 2025]. Tersedia di https://ethicsunwrapped.utexas.edu/case-study/blurred-lines-copyright